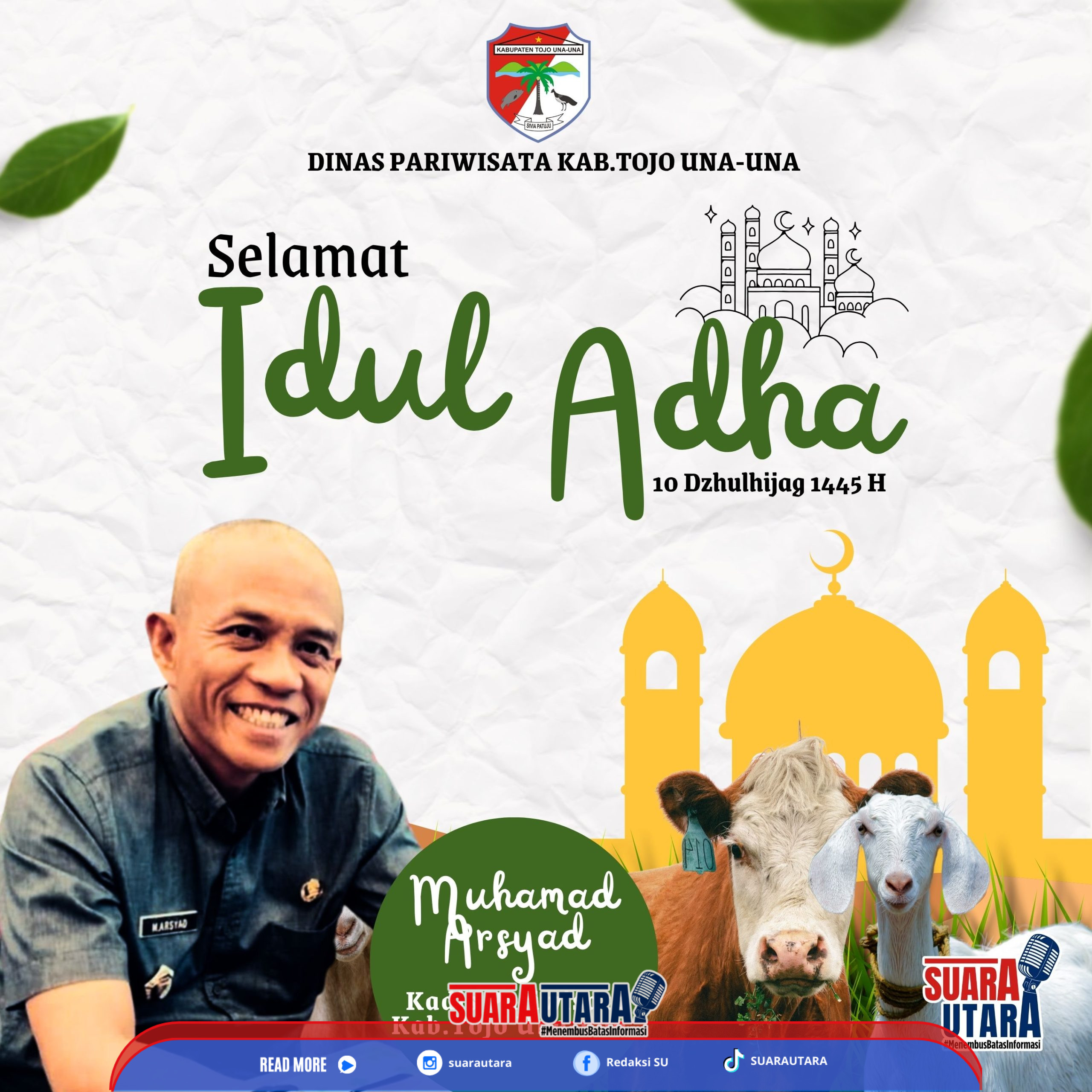Oleh Rastono Sumardi, S.Pd, M.E
Ketua Satupena Sulawesi Tengah
Di tengah gegap gempita program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis yang menelan anggaran Rp 335 triliun, sebuah pergeseran tektonik terjadi dalam arsitektur keuangan negara melalui APBN 2026. Pemerintah secara drastis memangkas ‘jatah’ Transfer ke Daerah (TKD) dari Rp 919,9 triliun menjadi Rp 693 triliun, sebuah langkah yang mengancam denyut nadi fiskal ratusan pemerintah daerah di seluruh nusantara. Namun, Jakarta berdalih bahwa dana yang mengalir ke daerah justru meroket hingga Rp 1.367 triliun melalui belanja langsung kementerian dan lembaga. Kebijakan ‘ganti pipa’ anggaran ini memicu perdebatan fundamental: apakah ini merupakan strategi brilian untuk efisiensi dan percepatan pembangunan, atau sebuah langkah resentralisasi terselubung yang menarik kembali kendali ke pusat dan menempatkan otonomi daerah yang telah dibangun selama dua dekade di ujung tanduk?
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Bayangkan seorang bupati di sebuah kabupaten kepulauan yang jauh dari ingar-bingar Jakarta. Selama bertahun-tahun, ia mengandalkan dana transfer dari pusat yang masuk ke kas daerah untuk memperbaiki jalan penghubung antar desa yang longsor, merenovasi atap sekolah dasar yang nyaris ambruk, atau sekadar memastikan puskesmas di pesisir tetap memiliki stok obat-obatan esensial. Dana itu, yang disebut Transfer ke Daerah (TKD), adalah napas bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya. Namun, pada tahun 2026, sebuah perubahan fundamental terjadi. Uang itu tidak lagi “mampir” ke rekening daerahnya. Sebaliknya, proyek perbaikan jalan kini dikerjakan oleh kontraktor pemenang lelang nasional dari Jakarta, dan bantuan untuk sekolah datang dalam bentuk barang yang dikirim langsung oleh sebuah kementerian. Sang bupati, yang tadinya adalah perencana, eksekutor, dan penanggung jawab utama pembangunan di wilayahnya, kini bergeser peran menjadi penonton—atau lebih tepatnya, fasilitator—di tanahnya sendiri.
Ini bukan sekadar fiksi atau hipotesis. Skenario ini adalah gambaran sederhana dari pergeseran paradigma raksasa yang sedang terjadi dalam arsitektur keuangan negara Indonesia, yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Sebuah kebijakan yang oleh pemerintah disebut sebagai langkah efisiensi dan percepatan pembangunan, namun oleh banyak pihak dianggap sebagai “revolusi senyap” yang berpotensi menggerus pilar otonomi daerah yang telah dibangun dengan susah payah sejak era Reformasi. Kebijakan ini memicu pertanyaan fundamental: Apakah ini sebuah langkah maju menuju pembangunan yang lebih efektif dan akuntabel, atau sebuah langkah mundur yang secara perlahan menarik kembali kewenangan ke pusat, mengikis esensi desentralisasi?
Untuk menjawabnya, kita perlu membedah apa yang sesungguhnya terjadi, mengapa ini dilakukan, dan apa dampaknya bagi masa depan pembangunan di lebih dari 500 provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.
- Guncangan Angka dan Pergeseran Pipa Anggaran
Untuk memahami skala perubahan ini, kita harus mulai dari angka. Selama lebih dari dua dekade, Transfer ke Daerah (TKD) telah menjadi urat nadi keuangan bagi sebagian besar pemerintah daerah (pemda). TKD adalah dana yang ditransfer langsung oleh pemerintah pusat ke kas daerah, yang kemudian dikelola sepenuhnya melalui APBD. Dana inilah yang menjadi tulang punggung pembiayaan untuk membayar gaji jutaan aparatur sipil negara (ASN) di daerah, mendanai operasional sekolah dan puskesmas, serta membiayai proyek-proyek infrastruktur lokal yang menjadi kewenangan daerah. Bagi banyak kabupaten/kota, porsi TKD bisa mencapai lebih dari 60%, bahkan 90%, dari total anggaran mereka.
Pada APBN 2025, pagu TKD ditetapkan sebesar Rp 919,9 triliun, sebuah angka kolosal yang mencerminkan betapa vitalnya peran dana ini. Namun, dalam rancangan awal APBN 2026, angka ini dipangkas secara dramatis. Pemerintah awalnya mengusulkan pagu TKD hanya sebesar Rp 650 triliun—level terendah dalam lima tahun terakhir. Usulan ini sontak memicu gelombang protes dan kekhawatiran dari para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Setelah melalui negosiasi alot di parlemen, angka tersebut akhirnya disepakati menjadi Rp 693 triliun.
Meskipun ada kenaikan dari usulan awal, angka akhir ini tetap menunjukkan penurunan tajam sebesar hampir 25% dari pagu tahun sebelumnya. Namun, yang lebih signifikan dari sekadar penurunan nominal adalah anjloknya proporsi TKD terhadap total belanja negara. Jika pada tahun-tahun sebelumnya TKD selalu mengambil porsi sekitar seperempat dari seluruh “kue” APBN, pada 2026 porsinya menyusut drastis menjadi hanya sekitar 18%. Ini adalah sinyal yang sangat kuat tentang adanya pergeseran fundamental dalam prioritas alokasi sumber daya nasional.
Lalu, ke mana perginya uang yang “hilang” dari TKD? Jawabannya terletak pada lonjakan fantastis alokasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang akan dieksekusi langsung di daerah-daerah. Pemerintah, melalui Menteri Keuangan, menegaskan bahwa total dana yang mengalir dan dibelanjakan di daerah justru meningkat pesat. Jika pada 2025 belanja K/L di daerah diestimasi sekitar Rp 900 triliun, pada 2026 angka ini meroket menjadi Rp 1.367 triliun.
Narasi resmi pemerintah sangat jelas dan konsisten: “Belanja ke daerahnya tidak turun, malah naik.” Argumennya adalah, seluruh APBN pada dasarnya adalah untuk rakyat Indonesia, tidak peduli siapa yang membelanjakannya, apakah itu pemerintah daerah melalui APBD atau kementerian dari Jakarta melalui APBN.
Di sinilah letak inti dari revolusi senyap ini. Ini bukan sekadar soal angka, tetapi soal perubahan “pipa” anggaran.
- Pipa Lama (Model TKD): Uang dari pusat mengalir ke sebuah “wadah” besar milik daerah, yaitu APBD. Daerah memiliki kewenangan penuh untuk merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan program sesuai dengan kebutuhan spesifik lokal yang dijaring melalui mekanisme partisipatif seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Akuntabilitasnya bersifat horizontal, dari kepala daerah kepada DPRD dan masyarakat setempat yang memilihnya.
- Pipa Baru (Model Belanja K/L): Uang tetap berada di “wadah” pusat, yaitu APBN. Kementerian di Jakarta-lah yang merancang program, melakukan lelang (seringkali secara nasional), dan menunjuk pelaksana proyek di lapangan. Pemerintah daerah, dalam model ini, hanya menjadi lokasi atau objek dari proyek tersebut. Akuntabilitasnya bersifat vertikal, dari satuan kerja di daerah ke kementerian di Jakarta, dan selanjutnya ke DPR RI.
Secara sederhana, jika sebelumnya pemerintah pusat memberikan uang kepada kepala keluarga (pemerintah daerah) untuk mengatur kebutuhan rumah tangganya, kini pemerintah pusat memilih untuk membeli dan mengirimkan langsung sembako, membayar tagihan listrik, dan merenovasi rumah untuk keluarga tersebut. Kepala keluarga tidak lagi memegang uangnya, meskipun kebutuhannya (secara teori) tetap terpenuhi. Pergeseran mekanisme ini secara efektif memindahkan lokus kendali perencanaan dan eksekusi secara masif dari daerah kembali ke pusat.
- Logika di Balik Langkah Drastis Jakarta
Setiap kebijakan besar, apalagi yang bersifat transformatif, tentu memiliki rasionalitasnya. Pemerintah mengajukan beberapa argumen kuat untuk membenarkan pergeseran paradigma ini. Memahami logika di balik keputusan ini penting untuk melihat gambaran yang utuh, melampaui sekadar pro dan kontra.
Alasan Pertama: Karpet Merah untuk Program Prioritas Nasional
Alasan yang paling menonjol dan paling sering dikemukakan adalah kebutuhan untuk menciptakan ruang fiskal yang cukup besar guna mendanai program-program ambisius dari pemerintahan baru. Fokus utamanya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menelan anggaran raksasa hingga Rp 335 triliun pada tahun 2026 saja. Untuk mendanai program berskala masif ini, pemerintah harus melakukan konsolidasi fiskal, yang dalam bahasa sederhana berarti “mengencangkan ikat pinggang” di pos-pos belanja lain dan mengalokasikannya kembali. TKD, sebagai salah satu komponen belanja terbesar dalam APBN, menjadi target yang tak terhindarkan.
Lebih dari sekadar mencari dana, pengalihan eksekusi ke pusat juga bertujuan untuk menjamin kepastian implementasi. Dengan mengambil alih pelaksanaan program-program di daerah, pemerintah pusat ingin memastikan program andalannya seperti MBG dapat berjalan mulus, terstandarisasi, dan akuntabel di seluruh pelosok negeri. Pemerintah tidak ingin mengambil risiko program unggulannya terhambat oleh birokrasi, kapasitas fiskal, atau kemampuan manajerial pemerintah daerah yang berbeda-beda. Ini adalah langkah untuk memastikan kontrol dan kepastian hasil.
Alasan Kedua: Misi “Spending Better” dan Efisiensi Anggaran
Selama bertahun-tahun, pemerintah pusat telah menyuarakan keprihatinan mendalam tentang kualitas belanja daerah. Ada beberapa “penyakit” kronis yang seolah sulit disembuhkan. Salah satunya adalah pola penyerapan anggaran yang cenderung lambat di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun, sebuah indikasi perencanaan yang kurang matang dan eksekusi yang tidak efisien.
Masalah lainnya adalah fenomena yang oleh para ekonom disebut flypaper effect. Ibarat kertas perekat lalat, dana transfer dari pusat seolah “menempel” di pemerintah daerah dan lebih banyak mendorong belanja konsumtif (seperti belanja pegawai, perjalanan dinas, dan operasional kantor) ketimbang digunakan sebagai pemicu untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melukiskan gambaran yang cukup suram: sekitar 92% kabupaten/kota di Indonesia masih berada dalam kategori “Belum Mandiri” secara fiskal. Banyak di antara mereka yang PAD-nya hanya mampu membiayai kurang dari 5% dari total kebutuhan belanjanya. Ketergantungan akut pada “uang dari pusat” ini sudah berada pada level yang sangat mengkhawatirkan.
Dari perspektif Jakarta, mengalihkan dana ke belanja K/L adalah sebuah jalan pintas untuk mengatasi inefisiensi ini. Dengan eksekusi yang terpusat dan terstandarisasi, pemerintah yakin dana APBN akan lebih efektif, efisien, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional. Ini adalah upaya konkret untuk mewujudkan prinsip spending better—bukan hanya sekadar membelanjakan (spending more), tetapi membelanjakan dengan lebih baik untuk menghasilkan outcome yang lebih terukur dan nyata bagi masyarakat.
Alasan Ketiga: Tafsir Baru atas Semangat UU Hubungan Keuangan Pusat-Daerah
Pemerintah juga membingkai kebijakan ini sebagai implementasi dari semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU ini sejatinya adalah sebuah reformasi besar yang dirancang untuk mengubah paradigma TKD dari sekadar “gelontoran uang” menjadi sebuah instrumen yang berbasis kinerja (performance-based).
UU HKPD memperkenalkan formula baru yang lebih canggih dan berorientasi pada hasil. Misalnya, Dana Alokasi Umum (DAU) tidak lagi dominan untuk belanja gaji, tetapi dihitung berdasarkan kebutuhan riil layanan dasar di daerah (seperti jumlah siswa atau pasien) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dana Alokasi Khusus (DAK) didesain ulang menjadi hibah spesifik (specific grant) yang difokuskan sepenuhnya untuk mencapai target-target prioritas nasional. Bahkan Dana Bagi Hasil (DBH) kini memiliki komponen 10% yang dialokasikan berdasarkan kinerja pemerintah daerah.
Menurut pemerintah, pengalihan belanja ke K/L adalah cara paling efektif untuk memastikan target-target kinerja yang diamanatkan dalam UU HKPD tersebut benar-benar tercapai. Namun, di sinilah letak ironi dan titik perdebatan utamanya. Banyak kritikus, termasuk para kepala daerah, berpendapat bahwa kebijakan ini justru bertentangan dengan ruh UU HKPD itu sendiri. UU tersebut dirancang untuk memperbaiki dan mendorong pemerintah daerah agar menjadi lebih akuntabel dan berkinerja melalui sistem insentif dan disinsentif, bukan untuk mengambil alih atau menghilangkan peran mereka.
Alih-alih membina dan memperkuat kapasitas daerah sesuai amanat reformasi desentralisasi, pemerintah pusat seolah mengambil jalan pintas dengan mengatakan, “Karena kinerjamu belum memuaskan, biar kami saja yang kerjakan.” Ini adalah manifestasi dari akumulasi “ketidakpercayaan” (distrust) pusat terhadap daerah, sebuah sentimen yang menjadi landasan tak terucapkan dari revolusi senyap dalam APBN 2026. Langkah ini, meskipun didasari oleh logika efisiensi yang kuat dari perspektif pusat, membuka babak baru yang penuh tantangan dan potensi disrupsi bagi daerah.
(Bersambung ke Bagian 2: Gempa di Daerah dan Masa Depan Otonomi)