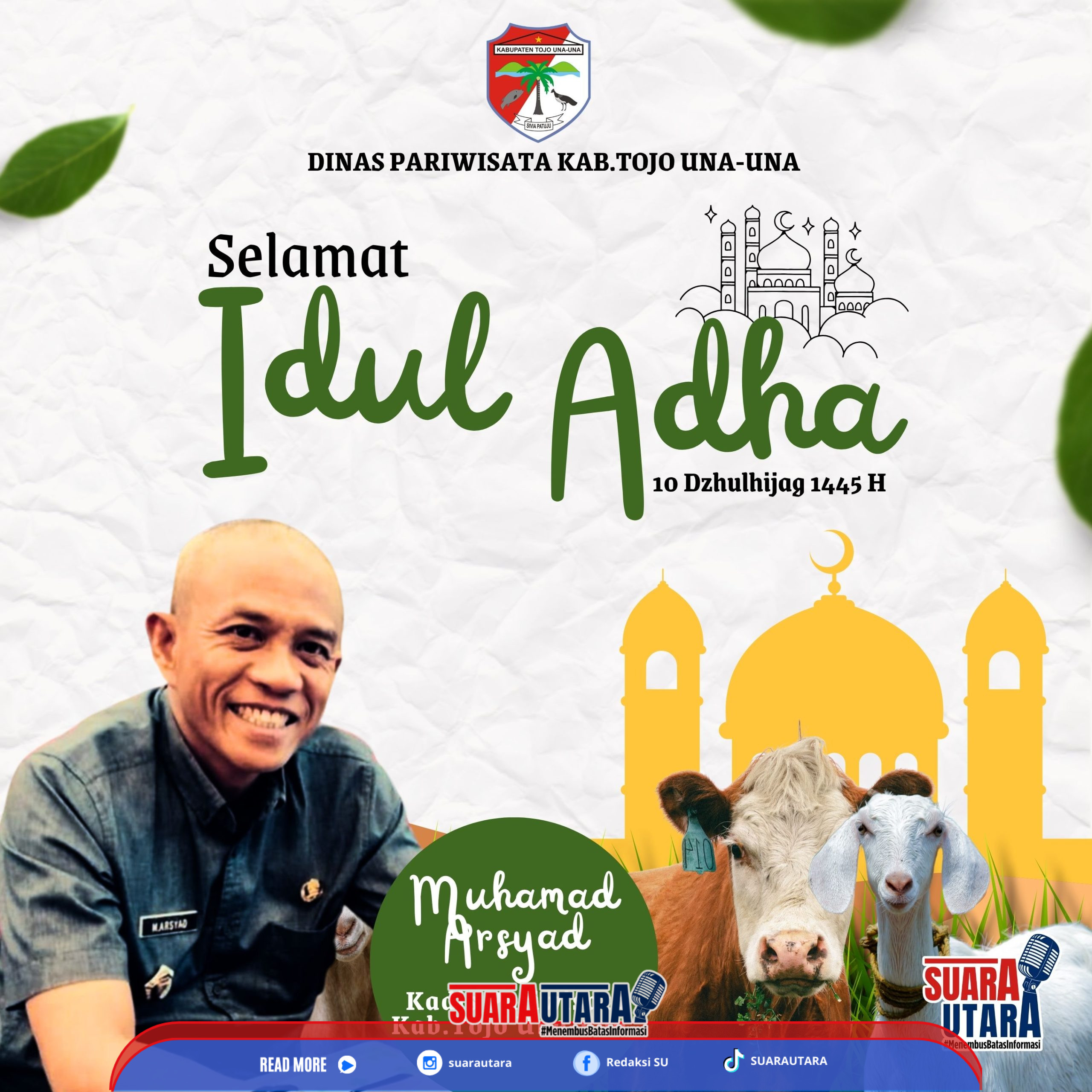Oleh : Rastono Sumardi, S.Pd, M.E
Ketua Satupena Sulawesi Tengah
Pada Bagian 1, kita telah membedah bagaimana APBN 2026 secara fundamental mengubah cara negara membiayai pembangunan di daerah. Pemangkasan drastis Transfer ke Daerah (TKD) dan pengalihannya menjadi belanja langsung oleh Kementerian/Lembaga (K/L) didasari oleh logika kuat dari pemerintah pusat: kebutuhan dana untuk program prioritas, upaya efisiensi anggaran (spending better), dan semangat akuntabilitas berbasis kinerja. Namun, sebuah kebijakan yang terlihat logis dari menara gading di Jakarta dapat terasa seperti gempa bumi ketika dampaknya dirasakan di ratusan daerah di seluruh Indonesia. Kini, kita akan menjelajahi rantai dampak dari kebijakan ini dan apa artinya bagi masa depan otonomi daerah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
- Gempa di Daerah dan Rantai Dampaknya
Jika logika dari Jakarta terdengar masuk akal dari perspektif efisiensi nasional, dampaknya di daerah berpotensi seperti gempa bumi yang memicu tsunami di tiga bidang utama: fiskal, ekonomi, dan yang paling krusial, tata kelola pemerintahan.
Guncangan Fiskal: Dari Gaji hingga Proyek Mangkrak
Dampak paling langsung dan paling menyakitkan dari pemangkasan TKD adalah tekanan hebat pada kas daerah. Pengurangan komponen krusial seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara langsung mengancam pos-pos belanja wajib yang paling mendasar. Banyak kepala daerah, dari gubernur hingga bupati, menyuarakan kekhawatiran serius tentang kemampuan mereka untuk membayar gaji ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tepat waktu.
Lebih jauh lagi, layanan publik dasar yang menjadi hak warga kini berada di ujung tanduk. Anggaran untuk operasional puskesmas, rehabilitasi ruang kelas yang rusak, dan pemeliharaan rutin infrastruktur lokal terancam dipangkas habis. Proyek-proyek yang sudah direncanakan dengan matang melalui Musrenbang, seperti perbaikan jalan kabupaten yang vital bagi petani, pembangunan jembatan antardesa, atau renovasi pasar tradisional yang menjadi jantung ekonomi lokal, berisiko besar untuk ditunda atau bahkan dibatalkan. Bagi daerah-daerah yang tingkat ketergantungan fiskalnya di atas 90%—yang menurut data BPK mencakup mayoritas kabupaten/kota di Indonesia—kondisi ini bukan lagi sekadar tekanan, melainkan ancaman nyata kelumpuhan fiskal.
Guncangan Ekonomi dan Sosial: Pajak Naik, Ekonomi Melambat
Menghadapi jurang fiskal yang menganga, pemerintah daerah tidak punya banyak pilihan. Jalan pintas yang paling mungkin ditempuh adalah menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara agresif. Cara termudah? Dengan menaikkan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Para pengamat ekonomi dan anggota parlemen telah memperingatkan bahwa kenaikan pajak yang tiba-tiba dan signifikan akan membebani dunia usaha lokal dan menggerus daya beli masyarakat. Warung kecil, pengusaha UMKM, hingga pemilik rumah akan merasakan dampaknya secara langsung. Jika tidak dikelola dengan komunikasi dan mitigasi yang baik, kebijakan ini berisiko memicu gejolak sosial, seperti yang sudah mulai terlihat di beberapa daerah.
Selain itu, belanja pemerintah daerah selama ini merupakan salah satu mesin penggerak utama ekonomi regional. Ketika pemda terpaksa mengerem belanjanya, efek domino akan terasa di seluruh ekosistem ekonomi lokal. Proyek konstruksi yang melambat akan mengurangi permintaan terhadap bahan bangunan dan tenaga kerja. Peredaran uang di masyarakat akan berkurang, dan pada akhirnya, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) akan meningkat, terutama di sektor-sektor yang sensitif terhadap belanja pemerintah. Alih-alih mengakselerasi pertumbuhan, kebijakan ini justru berisiko menyebabkan kontraksi ekonomi di tingkat lokal, sebuah paradoks dari tujuan awal pemerintah pusat.
Guncangan Tata Kelola: Mundurnya Jarum Jam Otonomi
Inilah dampak jangka panjang yang paling dikhawatirkan oleh para pejuang desentralisasi: erosi otonomi daerah. Ketika 83% dari kue belanja negara dikendalikan oleh pusat dan hanya 17% yang ditransfer ke daerah, semangat desentralisasi yang menjadi amanat Reformasi 1998 terasa seperti sedang ditarik mundur. Analis dari lembaga seperti Seknas FITRA menyoroti bahwa postur APBN ini secara efektif merupakan sebuah langkah resentralisasi fiskal yang nyata.
Muncul pula risiko serius ketidakselarasan perencanaan. Di satu sisi, pemerintah daerah memiliki Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun dari bawah ke atas (bottom-up) melalui Musrenbang, sebuah proses demokratis yang seharusnya menangkap aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat. Di sisi lain, kementerian di Jakarta datang dengan program-program nasional yang dirancang secara terpusat (top-down). Seberapa besar jaminan bahwa pembangunan jalan oleh Kementerian PUPR akan menyambung dengan jalan desa yang menjadi prioritas warga? Seberapa relevan program pelatihan dari pusat dengan kebutuhan spesifik industri lokal? Risiko tumpang tindih, program salah sasaran, dan proyek yang tidak sesuai dengan konteks lokal menjadi sangat besar.
Yang lebih berbahaya adalah potensi terciptanya insentif yang salah (moral hazard) bagi para pemimpin daerah. Jika sebelumnya seorang bupati atau wali kota diukur keberhasilannya dari kemampuannya mengelola APBD secara efektif untuk mewujudkan janji-janji kampanyenya, kini metrik kesuksesan bisa bergeser. Dengan ruang fiskal APBD yang semakin sempit, fokus mereka mungkin akan beralih dari manajemen pembangunan yang efektif menjadi lobi politik yang intensif di Jakarta. Tujuannya bukan lagi merancang program terbaik untuk warganya, tetapi “menarik” sebanyak mungkin proyek K/L ke wilayahnya. Ini akan melemahkan akuntabilitas kepala daerah kepada konstituen lokal dan justru memperkuat hubungan patronase dengan elite politik di tingkat pusat. Demokrasi lokal dan partisipasi publik bisa menjadi korban utamanya.
- Menavigasi Realitas Baru dan Mencari Jalan Keluar
Kebijakan ini adalah sebuah realitas baru yang harus dihadapi. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini baik atau buruk, tetapi bagaimana pemerintah pusat dan daerah dapat menavigasi perubahan ini untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi manfaatnya.
Tanggung Jawab Pemerintah Pusat
Beban pembuktian kini ada di pundak pemerintah pusat. Komitmen untuk menggelontorkan Rp 1.367 triliun melalui belanja K/L harus diwujudkan dengan implementasi yang sans serif, efisien, dan tepat waktu. Ini membutuhkan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi yang luar biasa kuat antara puluhan kementerian dengan 548 pemerintah daerah. Tanpa itu, dana raksasa ini hanya akan menjadi angka di atas kertas atau, lebih buruk lagi, menciptakan proyek-proyek “menara gading” yang tidak terintegrasi dan tumpang tindih. Pemerintah juga perlu menciptakan platform monitoring bersama yang transparan, di mana pusat dan daerah bisa sama-sama mengawasi realisasi dan dampak dari belanja K/L ini.
Strategi Adaptasi Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah tidak bisa hanya pasrah dan mengeluh. Ini adalah momen krusial yang menuntut adaptasi, inovasi, dan strategi yang cerdas. Sebuah contoh menarik datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menghadapi potensi pemotongan TKD sebesar Rp 2,8 triliun, mereka tidak hanya melayangkan protes. Secara proaktif, mereka menyusun daftar usulan program prioritas senilai Rp 10 triliun, lengkap dengan perencanaan teknis yang matang, dan mengajukannya ke berbagai kementerian terkait.
Langkah ini mengubah posisi mereka dari sekadar “penerima pasif” menjadi “pengusul aktif”. Mereka tidak menunggu bola, tetapi menjemput bola, menunjukkan bahwa daerah bisa bernegosiasi dan menyelaraskan kebutuhan lokalnya dengan agenda nasional. Namun, strategi ini menyoroti tantangan baru: kesenjangan kapasitas. Daerah-daerah kuat mungkin bisa melakukannya, tetapi bagaimana dengan kabupaten-kabupaten terpencil yang kapasitas perencanaannya terbatas?
Oleh karena itu, selain advokasi proaktif, reformasi internal di daerah menjadi sebuah keharusan. Momen ini harus menjadi cambuk untuk melakukan dua hal secara radikal: pertama, mencari sumber-sumber PAD baru yang inovatif dan berkelanjutan; kedua, melakukan efisiensi besar-besaran pada belanja birokrasi yang tidak produktif.
Kesimpulan: Pertaruhan Besar untuk Masa Depan Indonesia
Kebijakan redesain TKD dalam APBN 2026 adalah sebuah pertaruhan besar dengan konsekuensi yang sangat luas. Ini adalah langkah berani dari pemerintah pusat yang didasari oleh niat baik untuk mengakselerasi pencapaian prioritas nasional dan memperbaiki kualitas belanja negara. Jika berhasil, kita mungkin akan melihat target-target pembangunan tercapai lebih cepat dan terukur.
Namun, risikonya tidak kalah besar. Di sisi lain neraca, ada potensi erosi otonomi daerah, disrupsi layanan publik yang vital bagi masyarakat, dan penguatan tren resentralisasi fiskal yang dapat mematikan inovasi di tingkat lokal.
Pada akhirnya, keberhasilan atau kegagalan kebijakan ini akan sangat bergantung pada tiga faktor kunci: (1) kualitas implementasi belanja K/L di daerah dan kemampuannya untuk benar-benar menjawab kebutuhan lokal; (2) efektivitas jembatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah; serta (3) kapasitas adaptasi pemerintah daerah untuk bermanuver dalam lanskap fiskal yang baru. Tanpa strategi mitigasi yang kuat dan pengawasan yang ketat dari publik, risiko kebijakan ini dapat jauh lebih besar daripada peluangnya, dan cita-cita pemerataan pembangunan yang menjadi jantung dari semangat otonomi daerah justru bisa semakin jauh dari jangkauan.(*)