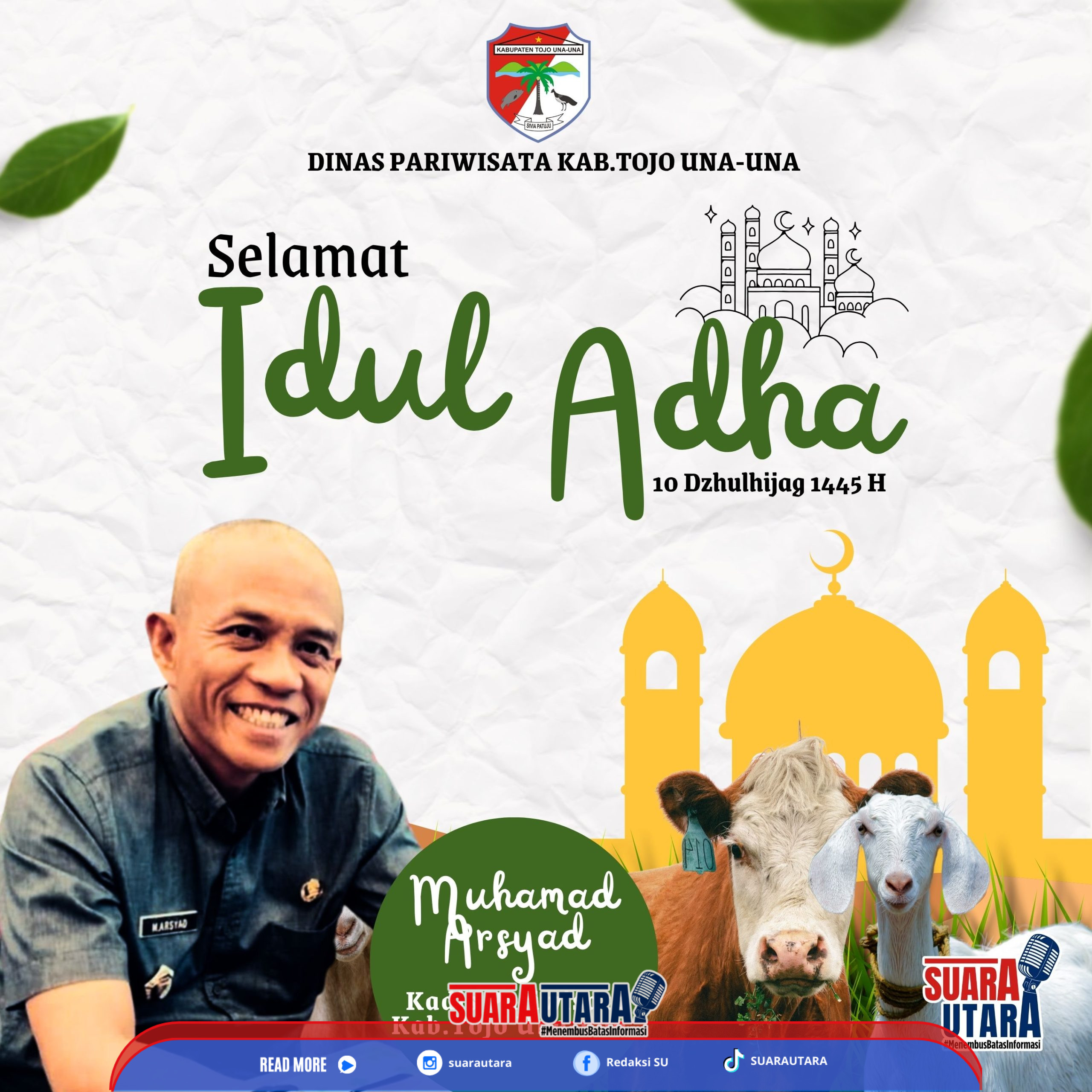Oleh : Rastono Sumardi
Ketua Satupena Sulawesi Tengah
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Di persimpangan jalur rempah Nusantara, di antara lengan-lengan Pulau Sulawesi, terhampar sebuah peradaban maritim yang kisahnya sering kali luput dari panggung besar sejarah Indonesia. Inilah Kesultanan Buton, sebuah negara yang selama lebih dari enam abad tidak hanya bertahan di tengah kepungan raksasa politik, tetapi juga berhasil membangun sebuah tatanan negara hukum yang luar biasa canggih, lengkap dengan konstitusi tertulis dan sistem parlementer yang mendahului zamannya. Jauh sebelum panji-panji republik berkibar, Buton telah menjadi laboratorium ketatanegaraan, sebuah bukti bahwa di jantung bahari Nusantara pernah berdenyut sebuah peradaban yang kosmopolit, tangguh, dan visioner.
Cikal Bakal Sebuah Kerajaan Maritim
Sejarah Buton berakar jauh sebelum Islam menancapkan pengaruhnya. Namanya telah disebut dalam Sumpah Palapa yang legendaris dari Patih Gajah Mada, sebuah pertanda awal akan posisi strategisnya. Namun, fondasi kerajaannya tidak dibangun oleh penaklukan, melainkan oleh konsolidasi damai para perantau. Menurut tradisi lisan, pada akhir abad ke-13, empat tokoh yang dikenal sebagai Mia Patamiana—Sipanjonga, Simalui, Sitamanajo, dan Sijawangkati—tiba dari Semenanjung Melayu. Mereka mendirikan permukiman-permukiman terpisah yang secara bertahap tumbuh dan berinteraksi.
Menyadari perlunya sebuah kepemimpinan terpusat untuk menjamin keamanan bersama, para pemimpin dari kelompok perantau ini, yang kini bergelar Bonto (menteri), bermusyawarah. Pada tahun 1332, mereka sepakat untuk menyatukan wilayah mereka di bawah satu mahkota. Namun, dalam sebuah langkah politik yang cerdas, mereka tidak memilih raja dari kalangan mereka sendiri. Mereka justru menobatkan seorang wanita terhormat bernama Wa Kaa Kaa sebagai ratu pertama.
Pilihan ini adalah sebuah masterstroke diplomasi. Wa Kaa Kaa bukan hanya figur lokal yang disegani, ia juga merupakan istri dari Si Batara, seorang bangsawan yang diyakini memiliki garis keturunan dari Kerajaan Majapahit. Dengan demikian, Kerajaan Buton yang baru lahir ini secara simultan mengklaim legitimasi dari dua kutub kekuatan utama di Nusantara: dunia Melayu di barat melalui para Bonto, dan hegemoni Majapahit di selatan melalui sang ratu. Sejak awal, Buton telah memposisikan dirinya sebagai simpul strategis di persimpangan peradaban.
Era awal kerajaan ini ditandai oleh kepemimpinan perempuan. Setelah Ratu Wa Kaa Kaa, takhta diwariskan kepada Ratu II Bulawambona. Kehadiran mereka di puncak kekuasaan menunjukkan sebuah tatanan sosial yang menghargai peran perempuan dalam politik. Namun, tradisi ini kelak akan berakhir seiring dengan datangnya fajar baru yang akan mengubah wajah Buton untuk selamanya.
Fajar Islam dan Lahirnya Sang Khalifah Kelima
Pada pertengahan abad ke-16, angin perubahan berembus kencang ke Buton. Seorang ulama kharismatik dari Johor, Syeikh Abdul Wahid, berhasil mengislamkan Raja Buton ke-6, La Kilaponto. Peristiwa ini bukan sekadar pergantian keyakinan pribadi sang raja; ia menjadi titik balik yang meredefinisi total identitas negara. Pada tahun 1542, Kerajaan Buton secara resmi bertransformasi menjadi Kesultanan Islam.
La Kilaponto, yang juga dikenal dengan nama Murhum, menjadi jembatan antara dua zaman. Ia adalah raja terakhir sekaligus sultan pertama. Setelah memeluk Islam, ia menyandang gelar yang luar biasa ambisius dan sarat makna politik: Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis.
Gelar “Sultan” adalah hal yang lazim, tetapi “Khalifatul Khamis” atau “Khalifah Kelima” adalah sebuah deklarasi kedaulatan yang menggema ke seluruh dunia Islam. Dalam tradisi Sunni, empat khalifah pertama setelah Nabi Muhammad—Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali—dikenal sebagai Khulafa’ur Rasyidin, model kepemimpinan ideal. Dengan mengklaim posisi sebagai “Khalifah Kelima,” Sultan Murhum secara efektif memposisikan Buton bukan sebagai kerajaan pinggiran, melainkan sebagai penerus sah dari tradisi kepemimpinan tertinggi Islam. Ini adalah pernyataan ideologis yang mengangkat martabat Buton, memberinya wibawa di panggung internasional, dan menjadi modal politik yang tak ternilai dalam menghadapi kekuatan-kekuatan regional yang lebih besar.
Transformasi ini bukan sekadar simbol. Islam dilembagakan secara sistematis ke dalam setiap sendi kehidupan negara. Jabatan Kadhi atau hakim agama dibentuk, dan hukum negara mulai dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang puncaknya adalah lahirnya sebuah konstitusi tertulis yang revolusioner.
Martabat Tujuh: Konstitusi Canggih dari Jantung Tasawuf
Keunikan terbesar Kesultanan Buton adalah sistem ketatanegaraannya. Buton bukanlah monarki absolut. Kekuasaan sultan dibatasi oleh undang-undang, dan ia diawasi oleh sebuah dewan perwakilan. Landasan dari semua ini adalah Undang-Undang Martabat Tujuh, sebuah konstitusi tertulis yang didasarkan pada ajaran tasawuf (mistisisme Islam) yang populer di Nusantara.
Ajaran Martabat Tujuh menguraikan tujuh tingkatan manifestasi Tuhan di alam semesta. Para negarawan Buton mengadopsi kerangka spiritual ini dan menerjemahkannya menjadi sebuah cetak biru negara. Bagi mereka, negara adalah cerminan tatanan kosmik, dan menjalankan pemerintahan adalah sebuah laku spiritual untuk mencapai keharmonisan. Konstitusi ini secara radikal mengubah sistem suksesi. Jika sebelumnya takhta diwariskan turun-temurun, kini seorang sultan harus dipilih dan disetujui oleh sebuah dewan legislatif yang dikenal sebagai Siolimbona (Dewan Sembilan Menteri).
Lembaga Siolimbona berfungsi layaknya parlemen modern. Sultan, sebagai kepala eksekutif, tidak berkuasa mutlak. Ia bertanggung jawab kepada dewan ini, yang berwenang memilih, melantik, menasihati, dan bahkan memberhentikan sultan jika ia melanggar konstitusi. Sistem ini lebih menyerupai monarki parlementer, sebuah konsep ketatanegaraan yang sangat maju pada masanya.
Keseimbangan kekuasaan ini tercermin dalam struktur sosial masyarakat yang terbagi menjadi empat golongan. Dua golongan teratas, Kaomu dan Walaka, memegang kunci kekuasaan, namun dengan peran yang terpisah secara cerdas untuk menciptakan sistem pengawasan dan keseimbangan (checks and balances).
Golongan Kaomu adalah kaum bangsawan keturunan raja pertama, Wa Kaa Kaa. Hanya dari golongan inilah seorang sultan dapat dicalonkan. Mereka memegang jabatan-jabatan eksekutif utama, seperti perdana menteri (Sapati) dan panglima perang (Kapitalao).
Di sisi lain, golongan Walaka adalah keturunan dari para pendiri kerajaan, Mia Patamiana. Mereka tidak berhak menjadi sultan, tetapi memegang kekuasaan legislatif dan yudikatif yang sesungguhnya. Merekalah yang mengisi dewan Siolimbona. Dengan demikian, Kaomu memegang takhta, tetapi Walaka memegang kendali atas konstitusi.
Prinsip supremasi hukum ini bukan sekadar teori. Bukti paling dramatis adalah kasus yang menimpa Sultan ke-8, Mardan Ali, pada pertengahan abad ke-17. Setelah melalui proses peradilan oleh dewan Siolimbona, ia terbukti bersalah menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar sumpahnya. Sesuai hukum yang berlaku, ia dijatuhi hukuman mati. Eksekusi terhadap seorang sultan yang sedang berkuasa adalah peristiwa yang hampir tak pernah terdengar di kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Kasus ini menjadi preseden yang meneguhkan bahwa di Buton, tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, bahkan seorang sultan sekalipun.
Pilar Kekuatan: Benteng, Niaga, dan Diplomasi Ular
Eksistensi Buton selama berabad-abad ditopang oleh tiga pilar: pertahanan yang kokoh, ekonomi maritim yang cerdik, dan diplomasi yang pragmatis.
Pilar pertahanan fisik Buton termanifestasi dalam wujud Benteng Keraton Wolio. Dibangun di atas bukit yang menghadap ke laut, benteng ini diakui oleh Guinness World Records sebagai benteng terluas di dunia, dengan luas mencapai 23 hektar. Pembangunannya dimulai pada abad ke-16 oleh Sultan La Sangaji dan disempurnakan menjadi bangunan permanen oleh Sultan Dayanu Ikhsanuddin. Benteng ini bukan sekadar struktur militer; ia adalah simbol negara. Dindingnya memiliki dua belas gerbang (Lawa), yang menurut keyakinan lokal melambangkan dua belas lubang pada tubuh manusia. Filosofinya jelas: negara adalah satu kesatuan organisme yang hidup, dan pertahanannya adalah tanggung jawab seluruh rakyatnya.
Dari segi ekonomi, Buton bukanlah tanah yang subur. Ia tidak menghasilkan rempah-rempah seperti Maluku. Kekuatannya terletak pada lokasinya yang strategis, tepat di jalur pelayaran yang menghubungkan barat dan timur Nusantara. Buton menjadi pelabuhan transit (entrepot) yang vital, tempat para pedagang singgah untuk mengisi perbekalan dan berlindung dari badai. Keamanan yang dijamin oleh benteng dan armada lautnya menjadikannya pilihan utama. Selain itu, para pelaut Buton dikenal mahir memanen hasil laut bernilai tinggi seperti mutiara dan teripang yang sangat diminati di pasar Tiongkok. Namun, ada sisi gelap dari kemakmuran ini. Buton juga menjadi salah satu pemasok utama dalam jaringan perdagangan budak regional, sebuah realitas kompleks di mana idealisme hukum yang tinggi hidup berdampingan dengan pragmatisme ekonomi yang keras.
Di panggung politik, Buton selalu terjepit di antara dua raksasa: Kesultanan Gowa di barat dan Ternate di timur. Untuk bertahan, Buton menjalankan kebijakan luar negeri yang digambarkan sebagai “sekutu-seteru”. Menyadari ia tak mampu sendirian, pada tahun 1613, Buton menjalin aliansi pertahanan dengan VOC (Kompeni Belanda). VOC akan membantu Buton jika diserang, dan sebagai imbalannya, VOC mendapat hak dagang. Namun, ini bukanlah ketundukan. Buton memandang VOC sebagai alat. Ketika kepentingan mereka selaras, mereka adalah “sekutu”. Namun, ketika VOC mulai mengancam kedaulatan Buton, mereka tak segan menjadi “seteru”.
Puncak dari kebijakan “seteru” ini adalah perlawanan heroik Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi pada pertengahan abad ke-18. Ia memandang perjanjian dengan VOC semakin merugikan dan menghina martabat kesultanan. Ketika sebuah kapal VOC dirampok di perairannya, ia menolak bekerja sama, memicu perang besar pada tahun 1755. Meski sempat terdesak, Himayatuddin memilih menyingkir dari istana dan melanjutkan perjuangan secara gerilya dari hutan dan pegunungan hingga akhir hayatnya. Perjuangannya yang gigih membuatnya dikenang dengan gelar Oputa Yi Koo (Tuanku yang Bergerilya di Hutan) dan diakui sebagai Pahlawan Nasional Indonesia.
Warisan Budaya dan Diaspora Sang Pelaut Ulung
Warisan Buton tidak hanya berupa benteng batu. Ia hidup dalam denyut budaya masyarakatnya. Wilayah kesultanan adalah sebuah mozaik linguistik yang kaya, dengan bahasa Wolio sebagai bahasa persatuan di istana, sementara bahasa lain seperti Cia-Cia berkembang di masyarakat. Tradisi adat seperti Pekande-kandea, sebuah upacara makan bersama untuk menyambut pahlawan perang, masih dilestarikan hingga kini. Dalam ritual ini, para gadis akan menyuapi para prajurit sebagai bentuk penghargaan, sebuah teater negara yang memperkuat ikatan patriotisme.
Sebagai peradaban maritim, jiwa orang Buton adalah laut. Mereka dikenal sebagai pelaut dan perantau ulung. Didorong oleh tradisi dan keterbatasan sumber daya di darat, mereka berlayar ke seluruh penjuru Nusantara, membentuk komunitas-komunitas diaspora di Maluku, Papua, hingga Kalimantan. Di tanah rantau, mereka membuka lahan, membangun perkampungan, dan menjadi simpul-simpul dalam jaringan perdagangan yang luas, menciptakan sebuah “persemakmuran Buton” informal yang membentang di lautan.
Senjakala dan Janji yang Tak Terpenuhi
Setelah lebih dari enam abad berdaulat, abad ke-20 membawa perubahan yang tak terelakkan. Sultan ke-38 dan terakhir yang memerintah, La Ode Muhammad Falihi, memimpin negerinya melewati masa-masa paling genting: senjakala kolonialisme, pendudukan Jepang, dan kelahiran Republik Indonesia.
Pada Februari 1950, dalam sebuah pertemuan di Malino, Presiden Soekarno bertemu dengan Sultan Falihi. Menurut catatan sejarah lisan, Soekarno menawarkan Buton status “daerah istimewa” jika bersedia bergabung dengan NKRI. Atas dasar janji inilah, Sultan Falihi dengan sukarela dan tanpa syarat menyatakan bergabung dengan republik yang baru lahir.
Namun, janji itu tak pernah terwujud. Status daerah istimewa tidak pernah diberikan. Bahkan, ketika Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk, ibu kota ditempatkan di Kendari, bukan di Baubau yang telah menjadi pusat peradaban selama berabad-abad. Era Kesultanan Buton secara definitif berakhir dengan wafatnya Sultan Falihi pada tahun 1960.
Meskipun sebagai negara ia telah tiada, warisan Kesultanan Buton tetap hidup. Benteng Keraton Wolio berdiri megah sebagai saksi bisu kejayaannya, menjadi kebanggaan nasional yang diusulkan sebagai warisan dunia. Tradisi, bahasa, dan identitas masyarakatnya terus berdenyut kuat. Kisah Buton adalah pengingat akan kekayaan peradaban Nusantara, sebuah studi kasus luar biasa tentang negara hukum maritim yang canggih, yang jejaknya menjadi bagian tak terpisahkan dari mozaik keindonesiaan.