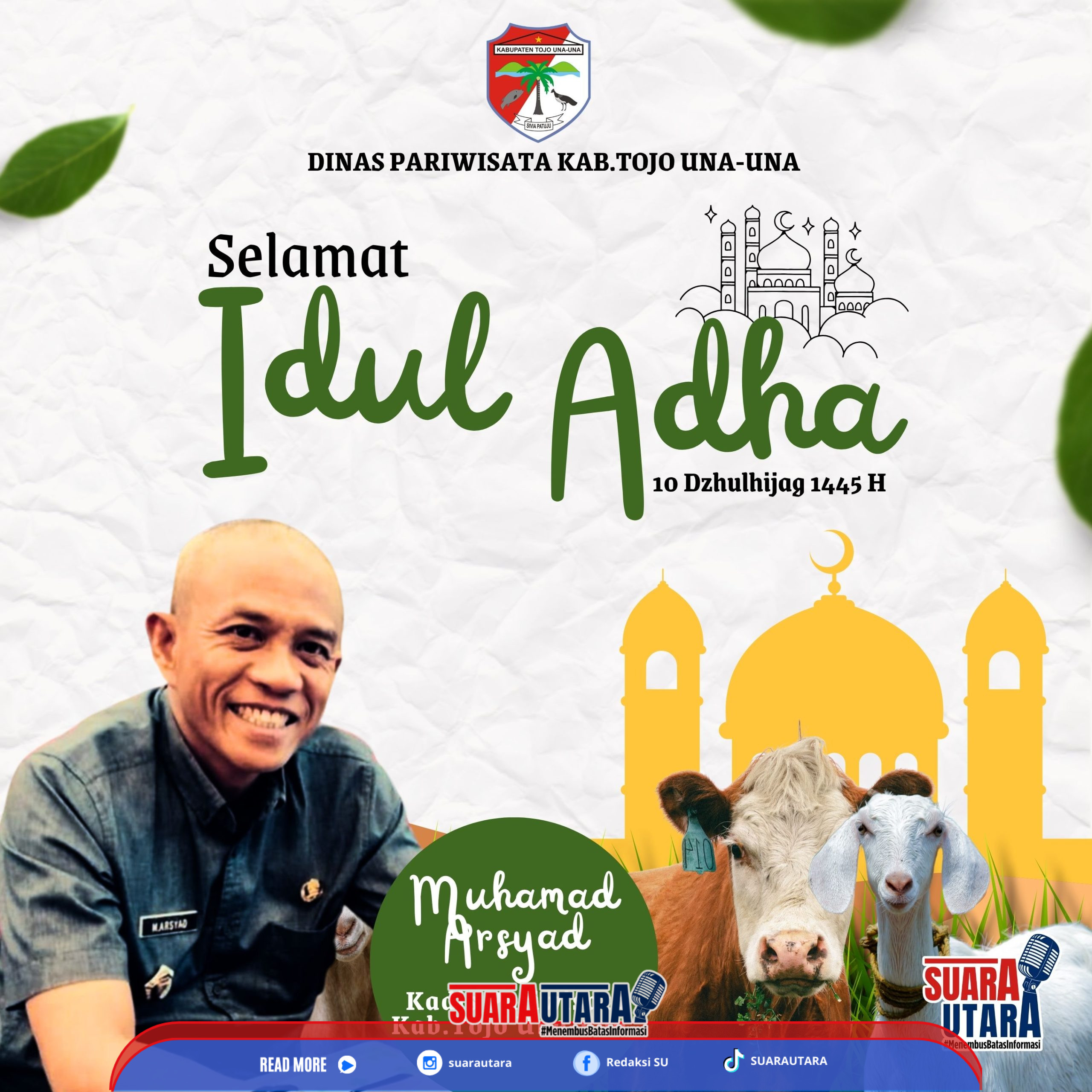Oleh : Rastono Sumardi
Ketua Persatuan Guru NU Banggai
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Di tengah deru modernitas dan lanskap pendidikan yang terus berubah, ada satu institusi yang berdiri teguh, seolah tak lekang oleh waktu. Ia adalah pesantren, sebuah ekosistem pendidikan yang DNA-nya terukir dalam sejarah panjang Nusantara. Lebih dari sekadar sekolah berasrama, pesantren adalah sebuah dunia—tempat di mana kitab-kitab kuno berdebu bertemu dengan laptop, di mana tradisi ribuan tahun berdialog dengan tantangan zaman digital, dan di mana karakter ditempa sekeras baja melalui disiplin spiritual dan intelektual selama 24 jam sehari.
Kisah pesantren bukanlah kisah yang dimulai dengan kedatangan Islam semata. Akarnya menancap jauh lebih dalam, pada tradisi-tradisi agung pra-Islam yang kemudian disirami dengan kearifan para sufi dan dirawat dengan cermat oleh para Walisongo. Perjalanannya adalah sebuah epik tentang adaptasi, perlawanan, dan inovasi. Dari bilik-bilik sederhana tempat para cantrik mengabdi pada resi, ia bertransformasi menjadi benteng perlawanan terhadap kolonialisme, melahirkan pahlawan-pahlawan bangsa. Dan hari ini, ia berevolusi menjadi kampus-kampus modern yang alumninya berkiprah di panggung dunia, dari menteri hingga novelis, dari cendekiawan hingga teknokrat.
Ini adalah perjalanan menelusuri jejak pesantren, sebuah mahakarya kebudayaan asli Indonesia yang terus-menerus menemukan kembali relevansinya, membuktikan bahwa tradisi bukanlah sauh yang menahan, melainkan kompas yang mengarahkan masa depan.
I. Gema dari Masa Lalu, Akar Pra-Islam dan Sentuhan Sufi
Untuk memahami jiwa sebuah pesantren, kita harus menarik benang sejarahnya kembali ke masa sebelum nama “Allah” dilantunkan di surau-suraunya. Secara linguistik, istilah “pesantren” sendiri adalah sebuah artefak sejarah. Ia berasal dari kata “santri”, yang oleh para ahli diyakini merupakan serapan dari kata shastri dalam bahasa Sansekerta, yang berarti “seorang ahli kitab suci Hindu”. Ini bukanlah kebetulan. Jauh sebelum Islam tiba, Nusantara telah memiliki sistem pendidikan residensial yang mapan, dikenal sebagai mandala atau ashrama.
Di tempat-tempat inilah para siswa, yang disebut cantrik, tinggal dan mengabdikan hidup mereka untuk belajar di bawah bimbingan seorang guru spiritual (resi). Pola hubungan guru-murid yang mendalam, penuh hormat (ta’dzim), dan pengabdian total ini menjadi cetak biru bagi relasi antara Kiai dan santri di kemudian hari. Para penyebar Islam awal, dengan kearifan luar biasa, tidak memberangus sistem ini. Sebaliknya, mereka melakukan “alih fungsi” yang brilian. Mereka mempertahankan wadah yang sudah dikenal masyarakat—sebuah lembaga pendidikan di mana murid tinggal bersama guru—namun mengganti isinya dengan ajaran tauhid, fikih, dan tasawuf. Pendekatan ini membuat Islam terasa bukan sebagai entitas asing, melainkan sebagai kelanjutan dan penyempurnaan dari tradisi spiritual yang telah ada. Inilah mengapa pesantren disebut sebagai indigenous culture, sebuah produk kebudayaan asli Indonesia.
Lapisan fondasi lainnya datang dari dunia tasawuf. Penyebaran Islam di Nusantara pada fase awal sangat kental dengan nuansa sufistik. Banyak Kiai perintis juga merupakan seorang guru sufi (mursyid) yang mendirikan tempat bagi para pengikutnya untuk berkumpul, berzikir, dan membersihkan jiwa. Tempat-tempat menyepi (uzlah) ini secara perlahan berevolusi. Selain amalan tarekat, sang guru mulai mengajarkan kitab-kitab klasik. Aktivitas “pengajian” inilah yang menjadi embrio dari sistem pendidikan pesantren yang lebih terstruktur, menanamkan DNA spiritual yang kuat yang masih terasa hingga kini.
II. Para Arsitek Peradaban, Jaringan Intelektual Walisongo
Jika tradisi pra-Islam dan kaum sufi meletakkan fondasinya, maka Walisongo-lah yang menjadi arsitek utamanya. Merekalah yang melembagakan, menyistematisasi, dan menyebarkan model pendidikan ini ke seluruh penjuru Jawa, menciptakan jaringan intelektual Islam pertama di Nusantara.
Syekh Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gresik) tercatat sebagai perintisnya, mendirikan pusat dakwah di Gresik yang memenangkan hati masyarakat melalui pelayanan sosial. Namun, Sunan Ampel-lah yang menjadikannya sebuah institusi besar. Pesantren Ampel Denta di Surabaya yang ia dirikan menjadi “kawah candradimuka” bagi para calon dai dan ulama. Dari sinilah lahir para wali lainnya, seperti Sunan Bonang yang mendirikan pesantren di Tuban dan Sunan Giri di Gresik.
Kejeniusan Walisongo terletak pada strategi dakwah kultural mereka. Mereka tidak membenturkan Islam dengan budaya lokal, tetapi justru merangkulnya. Sunan Bonang menggunakan gamelan untuk menarik massa, sementara Sunan Kalijaga menyisipkan pesan-pesan tauhid ke dalam lakon wayang kulit yang digemari masyarakat. Dengan cara ini, Islam tidak dirasakan sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari evolusi kebudayaan itu sendiri. Pesantren-pesantren yang mereka dirikan menjadi simpul-simpul dalam sebuah jaringan raksasa yang menyebarkan ilmu dan peradaban baru secara damai dan mengakar.
III. Monumen yang Hidup, Pesantren-Pesantren Tertua Penjaga Sejarah
Warisan para perintis itu kini menjelma menjadi monumen-monumen hidup—pesantren-pesantren berusia ratusan tahun yang masih kokoh berdiri, menjadi saksi bisu perjalanan bangsa.
Pesantren Al-Kahfi Somalangu, Kebumen (1475): Sang Patriark. Diakui sebagai pesantren tertua di Asia Tenggara, Al-Kahfi Somalangu adalah jembatan yang menghubungkan kita langsung ke era Walisongo. Didirikan oleh Syekh As Sayid Abdul Kahfi Al Hasani dari Yaman pada saat senja Kerajaan Majapahit, keberadaannya adalah bukti fisik transmisi keilmuan dari Timur Tengah ke jantung Jawa. Selama lebih dari 550 tahun, ia menjadi mercusuar Islam di pesisir selatan Jawa.
Pesantren Tegalsari, Ponorogo (sekitar 1742): Kawah Candradimuka Para Tokoh Bangsa. Pada abad ke-18, Tegalsari adalah pusat gravitasi intelektual dan spiritual di tanah Jawa. Kharisma pendirinya, Kiai Ageng Muhammad Besari, menarik ribuan santri hingga seluruh desa di sekitarnya berubah menjadi kompleks pendidikan raksasa. Daftar santrinya adalah daftar tokoh besar sejarah: pujangga agung Raden Ngabehi Ronggowarsito, pahlawan nasional Pangeran Diponegoro, hingga bapak pergerakan H.O.S. Cokroaminoto. Tegalsari adalah tempat di mana para elite kerajaan, pejuang, dan pemikir ditempa. Dari rahimnya pula, kelak lahir para pendiri Pondok Modern Gontor.
Pesantren Sidogiri, Pasuruan (1745): Simbol Ketahanan. Didirikan oleh Sayyid Sulaiman, seorang keturunan Sunan Gunung Jati, kisah Sidogiri dimulai dengan babat alas di tengah hutan belantara. Selama lebih dari 275 tahun, ia terus bertahan dan beradaptasi, menjadi contoh sempurna bagaimana sebuah institusi tradisional mampu menavigasi perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.
Pesantren Jamsaren, Surakarta (1750): Cermin Dinamika Politik. Lahir atas dukungan Keraton Surakarta di masa Pakubuwono IV, Jamsaren menunjukkan hubungan simbiosis antara pesantren dan kekuasaan. Namun, loyalitasnya diuji saat Perang Jawa. Jamsaren menjadi basis pendukung Pangeran Diponegoro, yang berakibat fatal. Setelah Diponegoro ditangkap, Belanda menghancurkan pesantren ini, memaksanya “mati suri” selama hampir 50 tahun. Kebangkitannya kembali di bawah Pakubuwono X menunjukkan betapa vitalnya peran pesantren bagi masyarakat, melampaui pasang surut politik.
Pesantren Buntet, Cirebon (1750): Benteng Perlawanan. Buntet lahir dari sebuah protes. Pendirinya, Mbah Muqoyyim, adalah seorang Mufti Keraton Cirebon yang memilih meninggalkan jabatannya karena muak melihat keraton berkompromi dengan penjajah Belanda. Dengan mendirikan pesantren di luar tembok istana, ia membangun sebuah pusat otoritas moral alternatif. Sejak awal, Buntet memposisikan diri sebagai benteng perlawanan budaya dan politik terhadap kolonialisme.

IV. Api dalam Sekam, Pesantren dan Perjuangan Kemerdekaan
Di bawah cengkeraman kolonialisme, saat institusi-institusi pribumi lainnya dilumpuhkan, pesantren menjadi suar otonomi. Di balik dindingnya, para Kiai meniupkan ruh jihad dan patriotisme. Mereka mengajarkan bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. Pesantren secara de facto menjadi pusat-pusat kaderisasi pejuang kemerdekaan.
Puncak dari peran ini terjadi pada 22 Oktober 1945. Di tengah ancaman kembalinya pasukan Sekutu (NICA), Hadratus Syekh KH. Hasyim Asy’ari, atas nama Nahdlatul Ulama, mengeluarkan Resolusi Jihad. Fatwa ini menyatakan bahwa membela tanah air dari penjajah adalah fardhu ‘ain, kewajiban bagi setiap Muslim.
Dampaknya dahsyat. Resolusi ini menjadi percikan api yang membakar semangat perlawanan. Ribuan santri dari seluruh Jawa Timur dan sekitarnya bergerak menuju Surabaya, membentuk laskar-laskar seperti Hizbullah dan Sabilillah. Merekalah tulang punggung dari Pertempuran 10 November 1945 yang heroik, sebuah pertempuran yang kini dikenang sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa ini mengukuhkan status pesantren sebagai salah satu pilar utama revolusi kemerdekaan, dan menjadi dasar ditetapkannya 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional.
V. Revolusi dari Dalam, Kelahiran Pesantren Modern Gontor
Memasuki abad ke-20, pesantren dihadapkan pada tantangan baru: sistem pendidikan sekuler model Barat yang diperkenalkan Belanda. Untuk menjawab tantangan ini, lahirlah sebuah revolusi dari dalam dunia pesantren itu sendiri, yang dipelopori oleh Pondok Modern Darussalam Gontor.
Didirikan pada tahun 1926 di Ponorogo oleh tiga bersaudara—K.H. Ahmad Sahal, K.H. Zainuddin Fananie, dan K.H. Imam Zarkasyi—Gontor menawarkan sebuah paradigma baru. Misi utamanya adalah meruntuhkan tembok dikotomi antara “ilmu agama” dan “ilmu umum”. Bagi Gontor, semua ilmu berasal dari Tuhan dan sama pentingnya.
Filosofi pendidikan Gontor terangkum dalam Panca Jiwa dan mottonya. Panca Jiwa adalah lima nilai yang menjiwai seluruh kehidupan pondok: Keikhlasan, Kesederhanaan, Berdikari (Kemandirian), Ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan Islam), dan Kebebasan. Sementara mottonya, “Berbudi Tinggi, Berbadan Sehat, Berpengetahuan Luas, Berpikiran Bebas”, meletakkan akhlak dan kesehatan sebagai fondasi untuk meraih ilmu yang luas, yang pada akhirnya akan melahirkan kemampuan berpikir merdeka.
Jantung sistemnya adalah Kulliyatul Mu’allimin al-Islamiyah (KMI), sebuah program pendidikan setara sekolah menengah selama enam tahun dengan kurikulum yang dirancang mandiri. Konsepnya radikal: “100% Agama, 100% Umum”. Fisika, Matematika, dan Biologi diajarkan dengan keseriusan yang sama seperti Fikih, Tafsir, dan Hadis. Bahasa Arab dan Inggris bukan sekadar mata pelajaran, melainkan bahasa komunikasi wajib sehari-hari. Pendidikan berlangsung total selama 24 jam, di mana setiap kegiatan—dari pramuka, latihan pidato, hingga olahraga—dirancang untuk membentuk karakter.
Dampak Gontor terasa di seluruh Indonesia. Jaringan alumninya menyebar luas, mengisi berbagai posisi penting di masyarakat. Mereka menjadi menteri seperti Lukman Hakim Saifuddin dan Hidayat Nur Wahid; cendekiawan berpengaruh seperti Nurcholish Madjid; pengusaha sukses seperti Muhammad Hilmy, pemilik jenang “Mubarok” Kudus; hingga sastrawan yang karyanya mendunia seperti Ahmad Fuadi, penulis novel Negeri 5 Menara. Lebih dari itu, ribuan alumni Gontor mendirikan pesantren-pesantren modern di daerahnya masing-masing, menyebarkan “virus” Gontor ke seluruh penjuru Nusantara, seperti Pondok Pesantren Darunnajah di Jakarta dan Al-Amien Prenduan di Madura.
VI. Dialektika Tradisi dan Modernitas di Abad ke-21
Hari ini, lanskap pesantren di Indonesia begitu beragam. Di satu sisi, ada pesantren salafiyah yang teguh mempertahankan tradisi pengkajian kitab kuning dengan metode sorogan dan bandongan, menjadi penjaga otentisitas khazanah keilmuan Islam klasik. Di sisi lain, ada pesantren khalafiyah (modern) yang sepenuhnya mengadopsi model Gontor.
Namun, ruang yang paling dinamis justru berada di tengah-tengah. Banyak pesantren besar dan bersejarah seperti Tebuireng dan Lirboyo kini menjadi pesantren kombinasi. Mereka mempertahankan kedalaman kajian kitab kuning sebagai ruh pendidikan, sambil secara paralel menyelenggarakan sekolah formal modern (MTs, MA) yang mengikuti kurikulum nasional. Model ini berupaya melahirkan sosok santri dengan kompetensi ganda: menguasai warisan klasik sekaligus siap bersaing di dunia modern.
Memasuki era digital, tantangan yang dihadapi pesantren semakin kompleks. Bagaimana mengintegrasikan teknologi tanpa menggerus nilai-nilai adab dan spiritualitas? Bagaimana memastikan kurikulumnya relevan dengan pasar kerja abad ke-21 yang menuntut kreativitas dan literasi digital?

Namun, di tengah tantangan itu, terbentang pula peluang besar. Di saat dunia mengeluhkan krisis karakter, model pendidikan holistik 24 jam ala pesantren menjadi jawaban yang relevan. Di tengah meningkatnya ekstremisme global, pesantren menjadi benteng utama Islam moderat (rahmatan lil ‘alamin). Dan semakin banyak pesantren yang bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan unit-unit usaha seperti agribisnis dan koperasi, membekali santri dengan keterampilan hidup yang nyata.
Perjalanan panjang pesantren adalah bukti dari kemampuannya untuk menari bersama zaman. Ia memegang teguh kaidah luhur: al-muhafazah ‘ala al-qadim al-salih wal-akhdzu bi al-jadid al-aslah—”memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik”.
Dari sebuah mandala kuno di tengah hutan Jawa hingga menjadi institusi pendidikan yang alumninya tersebar di seluruh dunia, pesantren telah membuktikan dirinya sebagai jantung peradaban Nusantara yang tak pernah berhenti berdetak. Ia adalah warisan, sekaligus masa depan. Sebuah laboratorium karakter bangsa yang akan terus melahirkan generasi-generasi yang tidak hanya cerdas otaknya, tetapi juga tercerahkan jiwanya, siap membangun Indonesia dan dunia.
Daftar Pustaka
Abdurrahman, M. N. (n.d.). Sejarah Singkat Buntet Pesantren. Scribd. Diakses dari https://id.scribd.com/document/864915581/Sejarah-Singkat-Buntet-Pesantren
Administrator. (2021, 12 November). Pesantren Tegalsari Ponorogo, Ponpes Pertama Di Ponorogo. Smazapo.org. Diakses dari http://smazapo.org/berita/detail/pesantren-tegalsari-ponorogo-ponpes-pertama-di-ponorogo
Adlani, N. (2023, 27 Maret). Peran Wali Songo dalam Penyebaran Islam di Nusantara. Adjar.grid.id. Diakses dari https://adjar.grid.id/read/543740913/peran-wali-songo-dalam-penyebaran-islam-di-nusantara?page=all
Al-Hikmah 2. (2009, 25 November). Sekilas Pondok Buntet Pesantren. Diakses dari https://alhikmahdua.net/sekilas-pondok-buntet-pesantren/
Al-Muanawiyah. (n.d.). Walisongo dan Perannya dalam Penyebaran Islam di Nusantara. Diakses dari https://almuanawiyah.com/walisongo-dan-perannya-dalam-penyebaran-islam-nusantara/
Alkhoirot.net. (2011, September). Daftar Pondok Pesantren Tertua di Indonesia. Diakses dari https://www.alkhoirot.net/2011/09/pondok-pesantren-tertua-indonesia.html
Beritasatu.com. (n.d.). 10 Pondok Pesantren Tertua di Indonesia, Ada yang Berusia 550 Tahun. Diakses dari https://www.beritasatu.com/nasional/2933461/10-pondok-pesantren-tertua-di-indonesia-ada-yang-berusia-550-tahun
Detik Hikmah. (n.d.). 10 Pesantren Tertua di Indonesia, Usianya Sudah Ratusan Tahun. Detik.com. Diakses dari https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-8172932/10-pesantren-tertua-di-indonesia-usianya-sudah-ratusan-tahun
Detik Jatim. (n.d.). 10 Pondok Pesantren Modern di Jawa Timur. Detik.com. Diakses dari https://www.detik.com/jatim/berita/d-6937479/10-pondok-pesantren-modern-di-jawa-timur
Endy, Z. (n.d.). Pesantren dan Tantangan Globalisasi. Junaidiyah.com. Diakses dari https://www.junaidiyah.com/pesantren-dan-tantangan-globalisasi/
Gontor.ac.id. (2023). Daftar Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren yang Mendapat Guru Pengabdian Putra Gontor Alumni Tahun 2023. Diakses dari https://gontor.ac.id/daftar-lembaga-pendidikan-pondok-pesantren-yang-mendapat-guru-pengabdian-putra-gontor-alumni-tahun-2023/
Gontor.ac.id. (n.d.). Pondok Tegalsari. Diakses dari https://gontor.ac.id/pondok-tegalsari/
Gramedia. (n.d.). 10+ Pesantren Terbaik di Indonesia, Mana Saja?. Gramedia Blog. Diakses dari https://www.gramedia.com/best-seller/pesantren-terbaik-di-indonesia/
Habibi, M. S. (n.d.). Deretan Orang Terkenal Ini Ternyata Alumni Pondok Modern Darussalam Gontor, Salah Satunya Sungguh Tak Terduga. Kompasiana. Diakses dari https://www.kompasiana.com/muhammadsahilhabibi3790/63214ef341ec7a7f32113a53/deretan-orang-terkenal-ini-ternyata-alumni-pondok-moderen-darussalam-gontor-salah-satunya-sungguh-tak-terduga
Hidayah, N. Z. (n.d.). Jamsaren1. Scribd. Diakses dari https://it.scribd.com/document/508426795/Jamsaren1
Hijra ID. (2023, 14 Agustus). Ini Peran Santri Dalam Kemerdekaan Indonesia, Kamu Wajib Tahu!. Hijra.id. Diakses dari https://hijra.id/blog/articles/peran-santri-dalam-kemerdekaan-indonesia/
Kompas.com. (2022, 17 Januari). 5 Pondok Pesantren Tertua di Indonesia, Sejarah Pendiri dan Lokasi. Diakses dari https://surabaya.kompas.com/read/2022/01/17/132000278/5-pondok-pesantren-tertua-di-indonesia–sejarah-pendiri-dan-lokasi?page=all
Krisdiyanto, G., et al. (2019). Sistem Pendidikan Pesantren dan Tantangan Modernitas. Jurnal Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan, 15(1), 11-21.
Kumparan. (n.d.). Peran Walisongo dalam Membangun Kerajaan Islam di Tanah Jawa. Diakses dari https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/peran-walisongo-dalam-membangun-kerajaan-islam-di-tanah-jawa-23gIAmSXHVZ
Laduni.id. (n.d.). Pesantren Buntet Cirebon. Diakses dari https://www.laduni.id/post/read/6817/pesantren-buntet-cirebon
Liputan6.com. (2025). 5 Rekomendasi Pesantren Modern di Bogor 2025, Ada yang Mirip Gontor. Diakses dari https://www.liputan6.com/islami/read/6106102/5-rekomendasi-pesantren-modern-di-bogor-2025-ada-yang-mirip-gontor
Liputan6.com. (n.d.). Alumni Pondok Modern Gontor: Menteri, Rektor, hingga Cendekiawan dan Budayawan. Diakses dari https://www.liputan6.com/islami/read/5067097/alumni-pondok-modern-gontor-menteri-rektor-hingga-cendekiawan-dan-budayawan
Merdeka.com. (n.d.). Deretan alumni Gontor yang jadi Dai kondang dan pentolan pemerintah. Diakses dari https://www.merdeka.com/peristiwa/deretan-alumni-gontor-yang-jadi-dai-kondang-dan-pentolan-pemerintah.html
MTs Al Islam Jamsaren. (n.d.). Sejarah. Diakses dari https://mtsalislamjamsaren.sch.id/?page_id=110
Muhajir. (2022). Kurikulum Kulliyatul Mu’allimin Al-Islamiyah (Kmi) Gontor Dan Disiplin Pondok Penumbuhkembang Karakter Santri. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2(1), 1-27.
Novandri, R. (2024, 12 Januari). Ini Daftar Pesantren Tertua di Indonesia. Radarbangsa.com. Diakses dari https://www.radarbangsa.com/khazanah/47665/ini-daftar-pesantren-tertua-di-indonesia
NU Cirebon. (2017, 5 Desember). Sejarah Pondok Buntet Pesantren Cirebon. Diakses dari https://nucirebon.or.id/blog/2017/12/05/sejarah-pondok-buntet-pesantren-cirebon/
Ponpes Darussalam Jatibarang. (n.d.). Mengenal Awal Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia. Diakses dari https://www.ponpesdarussalamjatibarangbrebes.com/mengenal-awal-sejarah-pondok-pesantren-di-indonesia/
Ponpesqu.id. (n.d.). Mengungkap Jejak Awal Sejarah Pondok Pesantren Pertama di Indonesia. Diakses dari https://ponpesqu.id/mengungkap-jejak-awal-sejarah-pondok-pesantren-pertama-di-indonesia/
Prasetyoadi, D. W. (2020, 27 Februari). Pesantren, dan Hubungannya dengan Sistem Pendidikan Pra Islam. Aswaja Dewata. Diakses dari https://www.aswajadewata.com/pesantren-dan-hubungannya-dengan-sistem-pendidikan-pra-islam/
Primago School. (n.d.). Bagaimana Konsep Pendidikan Karakter di Gontor?. Diakses dari https://primagoschool.com/bagaimana-konsep-pendidikan-karakter-di-gontor/
Putri M., K. (n.d.). Hari Santri: Lebih Dekat dengan Peran Santri. FBHIS UMSIDA. Diakses dari https://fbhis.umsida.ac.id/hari-santri-lebih-dekat-dengan-peran-santri/
Setiawanparusa. (2015, 17 Maret). 10 Tokoh Indonesia yang Pernah Nyantri di Gontor. Diakses dari https://setiawanparusa.wordpress.com/2015/03/17/10-tokoh-indonesia-yang-pernah-nyantri-di-gontor/comment-page-1/
Syihabuddin, M. (2025, 1 Agustus). Kilas Balik Perjuangan Santri dalam Kemerdekaan Republik Indonesia. Mubadalah.id. Diakses dari https://mubadalah.id/kilas-balik-perjuangan-santri-dalam-kemerdekaan-republik-indonesia/
Tidarislam.co. (n.d.). Menengok Aktivitas & Kurikulum Pesantren Gontor. Diakses dari https://tidarislam.co/menengok-aktivitas-kurikulum-pesantren-gontor/
Tirto.id. (n.d.). Mengenal Jenis-Jenis Pondok Pesantren dan Contohnya. Diakses dari https://tirto.id/mengenal-jenis-jenis-pondok-pesantren-dan-contohnya-gRe9
TribunMuria.com. (2023, 31 Januari). Ponpes Jamsaren Tertua di Solo, Pengikut Pangeran Diponegoro, Berdiri Sebelum Mataram Islam Pecah. Diakses dari https://muria.tribunnews.com/2023/01/31/ponpes-jamsaren-tertua-di-solo-pengikut-pangeran-diponegoro-berdiri-sebelum-mataram-islam-pecah
UIN Malang. (n.d.). Mengenal Dunia Pesantren. Diakses dari https://uin-malang.ac.id/r/131101/mengenal-dunia-pesantren.html
Wikipedia. (2025, 2 Agustus). Pesantren Tegalsari. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pesantren_Tegalsari
Zuhriyah, U. (2023, 20 Oktober). Pondok Pesantren Terbaik di Indonesia: Dari Jawa hingga Sumatra. Tirto.id. Diakses dari https://tirto.id/pondok-pesantren-terbaik-di-indonesia-dari-jawa-hingga-sumatra-gRhY